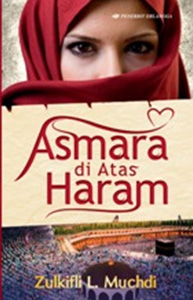 Oleh: Rosida Erowati Irsyad
Oleh: Rosida Erowati Irsyad
Dosen Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pendahuluan
Asmara di Atas Haram, karya Zulkifli L. Muchdi, mengisahkan dongeng dua sejoli Yasser dan Istiqomah, yang berlatar suasana haji di Makkah Al Mukarromah. Kisahnya menjadi lebih romantis dari Di Bawah Lindungan Ka’bah (karya HAMKA) karena agaknya sang penulis ingin segalanya berakhir bahagia, sesuai filosofi salah satu tokoh protagonisnya, Ferry Basthami, “hidup terus berputar seperti matahari mengitari bumi.” Tiada lagi tragedi dalam novel, yang harus membuat pembaca tenggelam dalam deraian dan isak.
Senandung asmara Yasser dan Istiqomah diawali dari pertemuan mereka sebagai para jawara tilawah dan tahfiz Al Quran tingkat nasional. Forum kejuaraan tilawah (MTQ) merupakan salah satu kejuaraan bergengsi yang mengangkat harkat dan derajat para pesertanya, apalagi para jawaranya. Dari forum inilah, benih cinta mulai bergayut di hati keduanya. Sebagai hadiah bagi para jawara MTQ, melaksanakan ibadah haji adalah yang paling diidamkan. Berhaji, memenuhi rukun Islam yang kelima, menjadikan keseluruhan ibadah dalam kehidupan seorang muslim afdol. Impian Yasser dan Isti untuk mampu melaksanakan ibadah haji terwujud di usia yang masih muda, berkat prestasi yang berhasil mereka capai. Di akhir perjalanan haji mereka, keduanya mengikat janji untuk menikah setelah usai melaksanakan tawaf wada, penutup ibadah haji. Kisah mereka menjadi romantika percintaan yang ideal, yang mampu memenuhi impian banyak muslim dan muslimah di seluruh belahan dunia.
Yasser Al Banjary, nama lengkap Yasser, digambarkan sebagai seorang pemuda Banjar, berprofesi wartawan freelance pada surat-surat kabar di Kalimantan Selatan, selain sebagai guru ngaji—yang dianggapnya sebagai amalan, bukan profesi—juga mahasiswa yang belum menuntaskan kuliah S1 nya karena terlalu sibuk dengan pencarian penghidupan. Lelaki yang digambarkan jujur dan teguh berpegang pada nuraninya ini juga telah menjadi yatim sejak duduk di bangku SMA (15 tahun), sehingga harus membantu ibunya menghidupi ketiga adiknya. Ia juga ditampilkan memiliki tampilan dan kecakapan fisik yang sangat baik. Tampan dan atletis dalam ukuran orang timur dengan tinggi badan 180 cm dan berat badan 70 kg, pandai bela diri taekwondo pula.
Gambaran tentang Yasser secara menyeluruh memperlihatkan model penokohan romantik, yang cenderung mengidealisasi semua aspek tokoh cerita. Seandainya penggambaran Yasser disampaikan dengan metafora-metafora yang lebih membuai imajinasi, saya mungkin akan tiba pada sosok ‘Indonesian Superman’, bukan dalam pengertian berlebihan kekuasaan, tapi penuhnya tokoh tersebut dengan sifat baik dan kemampuan fisik serta mental untuk menjaga sifat baiknya. Yasser is flawless, tanpa cacat fisik dan spiritual.
Muslim ideal sebagai stereotip tokoh
Istiqomah pun mengalami penggambaran yang sama idealnya. Seorang qariah, asisten dosen di salah satu fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cantik dan selalu berpenampilan modis. Juga tokoh Ferry Basthami, yang digambarkan sebagai anak Menteri Agama, Presiden Direktur empat perusahaan besar dan pengusaha travel haji plus, berparas tampan, perawakan atletis, duda yang tengah gundah mencari pengganti ibu bagi anaknya. Dan tokoh Dokter Eliza, yang digambarkan sebagai bidadari kembar dengan Isti, meski keduanya tak memiliki pertalian darah. Ada juga tokoh Evaterina Demitreva Ibrahimov, yang juga digambarkan berparas cantik dan berprestasi tinggi, seorang disainer berkebangsaan Ukraina, nominator Miss Universe, dan jatuh cinta pada Yasser karena ia melihat Yasser sebagai lelaki yang konsisten memegang teguh agamanya. Dan terakhir tokoh Sofia, putri pengusaha batubara dari Kalsel yang mengalami perubahan drastis dalam kehidupannya sejak kebangkrutan sang ayah, yang juga cantik semampai, dan baru sadar jatuh cinta pada mantan guru ngajinya, Yasser, setelah ia memecat gurunya itu.
Semakin banyak membaca novel yang bersandarkan agama, akan kita temukan tokoh dan latar yang lebih beragam, namun menggunakan resep penokohan yang sama, yaitu stereotip muslim ideal dalam setiap jenjang kelas sosial. Yasser mewakili kelas proletar, keluarga petani, yang ayahnya secara konsisten mendidik agar ia menjadi qari. Sedangkan Ferry mewakili kelas sosial menengah ke atas yang digambarkan tidak maruk dengan gadis cantik meski ia anak pejabat negara, kaya, dan sukses. Ferry tak tergoda untuk berpoligami, padahal masalah ini yang paling umum dihadapi oleh para lelaki dengan profil sepertinya. Isti, yang menjadi protagonis perempuan, terbentuk sebagai qariah karena secara genetik kedua orang tuanya juga qari dan qariah, serta memiliki pesantren, sehingga karakterisasi Isti dapat lebih ditonjolkan dari segi pengetahuan agama dan intelektualitasnya.
Campur tangan sang pengarang
Kualitas penokohan yang digambarkan oleh penulis yang juga mantan wartawan ini tidak diragukan lagi, cukup piawai menciptakan karakterisasi meski di sana sini terkadang saya tidak merasa puas dengan penceritaan yang digunakan. Pada beberapa bagian, terasa sekali tiba-tiba pribadi sang penulis mengambil alih porsi tokoh-tokohnya. Pada bagian 16, misalnya, halaman 172, yang mengungkapkan kenangan Yasser saat melakukan sai antara Bukit Safa dan Marwah.
“Yasser meneteskan air mata. Teringat betapa gigihnya daya juang Hajar demi mempertahankan hidup dan kehidupan. Refleks, ingatannya melayang kepada ibunya. Ayahnya meninggal puluhan tahun lalu. Waktu itu, Yasser duduk di bangku kelas satu Sekolah Menengah Atas (SMA)….”
Waktu yang digunakan sebagai detil untuk karakterisasi Yasser ini tidak akurat, menunjukkan bahwa pada bagian ini kemungkinan penulisnya secara pribadi mengambil alih porsi tokoh Yasser. Angka puluhan tahun lalu ini kemudian muncul lagi di bagian akhir cerita menjadi sepuluh tahun lalu, sehingga logika cerita menjadi lebih mungkin diterima.
Pada bagian-bagian lain, terkadang tokoh-tokoh berdialog terlalu panjang untuk ukuran dialog yang bisa kita terima dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muncul impresi seperti tengah monolog, yang sempat pernah ditampilkan oleh Kuntowijoyo dalam Khutbah di Atas Bukit saat sang tokoh protagonis, Barman, berpidato di depan umat pengikutnya, menjelang ia bunuh diri.
Pada bagian-bagian yang terkait dengan aktivitas berhaji, doa-doa bertaburan baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia, sehingga kecepatan penceritaan menjadi tertahan, seakan setiap doa dalam haji merupakan detil cerita yang tak dapat ditinggalkan. Teknik menahan atau digresi seperti ini terkadang membuat saya kehilangan momentum dengan cerita. Puisi dalam bentuk doa yang juga tampil dalam novel ini mampu mendukung dramatik, namun doa-doanya sendiri terasa terlepas meski sesuai dengan konteks penceritaannya, misalnya doa saat mengambil miqat, memulai tawaf, saat sai, dan saat jumrah. Doa-doa ini terkesan masih dikutip untuk memenuhi keutuhan latar suasananya, namun karena terkadang menjadi terlalu panjang, kita tak lagi mendapatkan pemaknaan atas doa itu sendiri. Pada bagian 8, bahkan, kutipan M. Quraish Shihab (h. 76) tanpa ada konteks cerita yang jelas tiba-tiba muncul, hanya untuk menjelaskan tentang makna miqat.
Konflik cerita sebagai sarana berwacana
Novel berlatar suasana haji ini sejak awal cerita menggunakan konflik seputar hati nurani dan godaan yang senantiasa dialami oleh setiap muslim dan muslimah. Masalah kejujuran, keberanian untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar, keteguhan dalam menaati perintah agama, menjaga hati dan pikiran agar tetap dalam syar’i menjadi konflik utama dalam dongeng dua sejoli ini.
Meski ada masalah yang sangat aktual dan spesifik tentang kebobrokan industri tambang batubara di Kalsel, masalah lemahnya dukungan pemerintah terhadap industri kecil, dilema tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang seolah terbuang dari tanah air dan terlecehkan di negeri orang, bahkan urusan lemahnya persatuan umat muslim sedunia hingga Yasser dan Isti harus mengusulkan Statement Namirah kepada Raja Arab Saudi; konflik-konflik ini sebatas menjadi wacana dalam kisah Asmara di Atas Haram.
Yang mengikat semua tokoh untuk bersatu adalah naungan Ka’bah dan ibadah haji. Jika ibadah haji tuntas ditunaikan, problem individu dan sosial akan selesai dengan lahirnya individu-individu baru yang tercerahkan dan mau berkomitmen pada cita-cita Islam Rahmatan lil Alamin. Sosok-sosok seperti Yasser dan Isti yang menyadari kekurangan di dalam agamanya sendiri, terlahir dan berniat memperbaiki kondisi ini mulai dari diri mereka sendiri. Hingga cita-cita mereka terungkap di bagian akhir, cita-cita yang realistis dan dapat menjadi penyemangat, cita-cita mulia, yaitu menikah dalam naungan agama Islam, dan mencapai haji mabrur, mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat.
Penutup
Fiksi dapat menjadi alat penyalur pesan yang efektif. Asmara di Atas Haram karya Zulkifli L. Muchdi membuktikan bahwa latar suasana haji dapat digunakan sebagai bahan untuk menciptakan fiksi yang inspiratif. Kekurangan dalam penceritaan tidak mengurangi kelebihannya sebagai novel Islami yang bertujuan menguatkan sandaran keimanan kaum muslimin. Suasana dan detil peristiwa haji dapat digambarkan dengan baik oleh sang penulis, meski penghalusan bahasa, khususnya pengayaan metafora, ketepatan ejaan dan tanda baca, perlu ditingkatkan lagi. Kekuatan prosa sebagai fiksi panjang yang mengandalkan wacana sangat bertopang pada ragam bahasa tulis, yang juga menuntut kedisiplinan dalam memperhatikan aspek-aspek ini.











